PENYELARASAN TASAWUF DENGAN SYRI’AT DALAM PEMIKIRAN AL-GHAZALI
Oleh: M. Idsris Yusuf dan Hendriyanto al-Mandari
Aku teliti aqidah setiap kelompok dan menyingkap
rahasia cara pikir setiap golongan, agar aku bisa membedakan antara
kelompok yang memperjuangkan kebenaran dan kelompok yang memperjuangkan
kebathilan, agar bisa membedakan antara pengikut sunnah dan pencipta
bid’ah”.
- A. Al-Ghazali dan Tasawuf
Bahwa
Al-Ghazali adalah ulama’ besar yang sanggup menyusun kompromi antara
syari’at dan hakikat atau tasawuf menjadi bangunan baru yang cukup
memuaskan kedua belah pihak, baik dari kalangan syar’I ataupun lebih-lebih kalangan sufi.[1]

Berbagai
macam buku yang membahas tentang sepak terjang Al-Ghazali yang tumbuh
kembang pada masa dimana banyak muncul mazhab dan goolngan. Ketika itu,
beragam kecenderungan berfikir, baik yang bernuansa agama maupun rasio,
berbenturan dan beradu argumentasi. Al-Ghazali merasakan dirinya di
antara mazhab yang terpecah belah, kelompok-kelompok perusak, filsafat
asing dan bid’ah-bid’ah pemikiran. Sehigga tergambar dalam bait
kata-katanya yang begitu menggugah hati dengan gemuruh semangat dan
keberanian;
“ketika masih muda, aku menyelami
samudera yang dalam ini. Aku menyelaminya sebagai penyelam handal dan
pemberani, buka sebagai penyelam penakut dan pengecut. Aku menyerang
setiap kegelapan dan mengatasi semua masalah, menyelami kegoncangan. Aku
teliti aqidah setiap kelompok dan menyingkap rahasia cara pikir setiap
golongan, agar aku bisa membedakan antara kelompok yang memperjuangkan
kebenaran dan kelompok yang memperjuangkan kebathilan, agar bisa
membedakan antara pengikut sunnah dan pencipta bid’ah”.[2]
Dengan
demikian tidak ayal al-Ghazali merasakan dirinya berhadapan dengan
samudera luas, dengan gulungan ombak yang sangat dahsyat dan dalam. Dia
tidak memposisikan dirinya sebagai “penggembira” yang hanya
ikut-ikutan dalam gelombang dahsyat itu. Dia tidak merasa takut terhadap
luasnya samudera, kedalaman dasar samudera dan besarnya gelombang. [3]
Dasar ajaranTasawuf adalah cinta rindu untuk berhubungan dengan kekasihnya Allah SWT, dan berasik-maksyuk dengan Dia.[4]
Perkembangan yang cukup menarik adalah timbulnya kesadaran dari dalam
untuk memoderasi ajaran Tasawuf, dan untuk mengeliminir konflik antara syari’at dan tasawuf atau hakikat.
Upaya ini walaupun tidak akan berhasil memuaskan sepenuhnya, namun
cukup konstruktif dan positif. Pertentangan antara hakikat dan syari’ah
bisa diperkecil. Namun sebaliknya menimbulkan konflik ke dalam antara
golongan yang lebih ortodoks dengan sufisme murni yang lebih heterodoks
(pantheis). Disamping itu kelemahan yang mendasar dari kompromi ini,
umumnya terletak pada penghargaan terhadap Tasawuf (hakikat) selalu dipandang lebih tinggi dari Syari’at.
Al-Ghazali misalnya membagi iman menjadi tiga tingkat, dan yang paling
tinggi adalah para arifin (sufi). Ajaran ini diterangkan sebagai
berikut;
“Keimanan tingkat awal, imannya orang-orang awam, yakni iman dasar taklid.
Tingkat kedua, imannya para mutakallimin (teolog), atas dasar campuran (taklid) dengan sejenis dalil.
Tingkatan ini masih dekat dengan golongan awam.
Tingkat ketiga, imannya para arifin (sufi) atas dasar pensaksian secara langsung dengan perantara nurul yaqin.(ihya’ ‘ulumuddin, III, hal. 15).[5]
Setelah
Al-Ghazali melihat bahwa ahli ilmu kalam, filosof dan kaum Batiniyah
tidak mampu mengantarkannya mencapai keyakinannya dan hakikat, maka dia
melirik tasawuf yang menurut pandangannya adalah harapan terakhir yang
bisa memberikannya kebahagiaan dan keyekinan. Ia mengatakan, “setelah aku mempelajari ilmu-ilmu ini (kalam, filsafat, dan ajaran bathiniyah), aku mulai menempuh jalan para sufi.”[6]
Para sufi banyak berbicara tentang kasyf dan mu’ayanah,
mampu berhubungan dengan alam malakut dan belajar darinya secara
langsung, mampu mengetahui lauhul-mahfuzh dan rahasia-rahasia yang
dikandungnya. Namun, bagaimanakah caranya agar manusia mampu mendapatkan
kasyf dan mu’ayanah? Para sufi menjawab, caranya dengan menuntut ilmu
dan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Al-Ghazali mengatakan, “Aku tahu bahwa tarekat mereka menjadi sempurna dengan ilmu dan amal”[7]
Jalan pertama, yaitu Ilmu. Al-Ghazli mulai mendapatkan ilmu kaum sufi dari kitab Qut Al-Qulub Mu’amalah Al-Mahbub karya Abu Thalib Al-Makki dan kitab Ar-Ri’ayah li Huquq Allah karya Harits Al-Muhasibi, serta ucapan-ucapan pucuk pimpinan sufi semisal Al-Junaidi, As-Syibli, Al-Busthami, dan lain-lain. Al-Ghazali mengatakan, “Mendapatkan
ilmu Tasawuf bagiku lebih mudah dari pada mengamalkannya. Aku mulai
mempelajari ilmu kaum sufi dengan menelaah kitab-kitab dan ucapan-ucapan
guru-guru mereka. Aku mendapatkan ilmu dengan cara mendengar dan
belajtar. Nampaklah bagiku bahwa keistimewaan guru besar sufi tidak
mungkin digapai dengan cara belajar, tetapi dengan cara dzauq, hal, dan
memperbaiki sifat diri.”
Jalan kedua, yaitu dengan cara Tahalli (menghias diri dengan sifat-sifat utama), Tkhalli (membersihkan
firi dari sifat-sifat yang rendah dan tercela) agar manusia dapat
memberesihkan hati dari pikiran selain Allah dan menghias hati dengan
berzikir kepadaNya. Al-Ghazalai mengatakan, “Adapu manfaat yang
dicapai dari ilmu sufi adalah terbuangnya aral yang merintangi jiwa,
mensucikan diri dari akhlaknya yang tercela dan sifatnya yang kotor,
hingga dengan jiwa yang telah bersih itu hati menjadi kosong dari selain
Allah dan dihiasi dengan dzikir kepada Allah.”[8]
Di dalam kitab-kitab Ihya’ ‘Ulumuddin, Al-Ghazali menulis, “Bagi
hati, ada dan tiadanya sesuatu adalah sama. Lantas, bagaimanakah hati
meninggalkan semua urusan Dunia? Demi Allah, ini adalah jalan yang
sangat sukar; jarang sekali ada manusai yang sanggup melakukannya”[9]
Cukup
lama Al-Ghazali berada dalam situasi tarik menarik antara dorongan hawa
nafsu dan panggilan akhirat, hingga akhirnya ia merasa dirinya tidak
lagi harus memilih, tetapi dipakasa untuk meninggalkan Bagdad. Kini
lidahnya menjadi berat dan dirinya merasa bosan mengajar. Keadaan ini
membuat hatinya sedih dan kondisi fisiknya lemah, sampai-sampai dokter
putus asa mengobatinya. Para dokter mengatakan, “Penyakitnya
bersumber dari hati dan merembet ke tubuhnya. Penyakitnya tidak bisa
diobati kecuali mengistirahatkan pikiran dari factor-faktor yang
membuatnya sakit”[10]
“Disaat
menyadari ketidak mampuan dan semua upaya telah gagal, akupun mau tak
mau harus kembali kepada Allah dalam keadaan yang terpaksa dan tidak
mempunyai pilihan lagi. Allah-yang menjawab doa yang terpaksa jika
berdoa-mengabulkan niatku, sehinngga kini terasa mudah bagiku
meninggalkan pangkat, harta, anak, dan teman.”[11]
Sesudah mengalami masa-masa keraguan yang cukup rumit, baik dalam filsafat ataupun penggunaannya dalam Ilmu Kalam, akhirnya justru mendapatkan kepuasan dalam penghayatan kejiwaan dalam Sufisme, yakni mempercayai kemutlakan dalil kasyfi.[12]
Hal ini merupakan keunikan-keunikan atau keanehan al-Ghazali. Mungkin
karena pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat Persi masa itu yang
merupakan lahan yang subur bagi perkembangan pemikiran dan kehidupan
sufisme. Agaknya beliau telah sejak kecil punya penilaian positif
terhadap ajaran sufisme. Karena memang beliau melihat dan menghayati
betapa institusi tasawuf dapat memperdalam keyakinan dan perasaan agama
yang mendalam, serta dapat membina akhlaq yang luhur. Dan ternyata
akhirnya Al-Ghazali jadi propagandis sufisme yang paling bersemangat dan
paling sukses. Misalnya, tetntang kehidupan para sufi dan tasawuf yang
digambarkannya:
“Sungguh aku mengetahui secara
yakin bahwa para sufi itulah orang-orang yang benar-benar telah
menempuh jalan Allah SWT, secara khusus. Dan bahwa jalan mereka tempuh
adalah jalan yang sebaik-baiknya, dan laku hidup mereka adalah yang
paling benar, dan akhlaq adalah yang paling suci. Bahkan seandainya para
ahli pikir dan para filosof yang bijak, dan ilmu para ulama yang
berpegang pada rahasia syari’at berkumpul untuk menciptkan jalan dan
akhlaq yang lebih baik dari apa yang ada pada mereka(para sufi) tidak
mungkin bisa menemukannya. Lantaran gerak dan diam para sufi, baik lahir
ataupun bathin, dituntun oleh cahaya kenabian. Dan tidak ada cahaya
kenabian diatas dunia ini, cahaya lain yang bisa meneranginya.”(mungqidz min al-Dlalal, hal, 31). [13]
Kemudian
soal pendalaman perasaan agama dan pemantapan iman, Al-Ghazali melihat
bahwa tasawuf adalah sarana yang hebat untuk untuk mendukung bagi
pendalaman rasa agama (spiritualitas Islam) dan untuk memantapkan dan
menghidupkan iman. Dengan Ilmu kalam orang baru bisa mengerti
tentang pokok-pokok keimanan, namun tidak bisa menanamkan keyakinan yang
mantap dan menghidupkan pengalaman agama. Oleh karena itulah Tasawuflah sarana yang paling hebat untuk mengobati penyakit formalism dan kekeringan rasa keagamaan ini menurut Al-Ghazali.[14]
Yang
menjadi masalah kemudian, bagaimana cara mengawinkan dan
mengkrompromikan tasawuf dengan syari’at? Atau dengan kata lain
bagaimana mengkompromokan syari’at dan hakikat sehingga keduanya tidak
saling menggusur, akan tetapi justru saling mendukungnya. Persoalan
inilah yang telah cukup lama diangan-angankan oleh para sufi sendiri,
bagaimana cara menjembatani dua system yang tumbuh berdampingan yang
sering memancing konflik yang cukup tajam.[15]
Adapun fungsi hakikat itu sendiri terhadap syari’at adalah sebagaimana digamabarkan Imam Al-Qusyairi di dalam risalahnya yaitu;
“Syari’at
itu perintah untuk melaksanakan ibadah, sedang hakikat menghayati
kebesaran Tuhan (dalam ibadah). Maka setiap syari’at yang tidak
diperkuat hakikat adalah tidak diterima; dan setiap hakikat yang tidak
terkait dengan syari’at tak menghasilkan apa-apa. Syari’at datang dengan
kewajiban pada hamba, dan hakikat memberitakan ketentuan Tuhan.
Syari’at memerintahkan mengibadahi Dia, hakikat meyaksikannya pada Dia.
Syari’at melakukan yang diperintahkan Dia, hakikat menyaksikan
ketentuannya, kadar-Nya, baik yang tersembunyi maupun yang di luar.
(Risakah Qusyairiyah. Hal, 46)[16]
Disini,
Al-Ghazali berupaya membersihkan tasawuf dari ajaran-ajaran asing yang
merasukinya, agar tasawuf berjalan di atas koridor Al-Qur’an dan
As-Sunnah. Ia menolak paham Hulul dan Ittihad
sebagaimana yang di propagandakan oleh al-Hallaj dan lainnya. Al-Ghazali
hanya menerima tasawuf Sunni yang didirikan diatas pilar Al-Qur’an dan
As-Sunnah. Ia berusaha mengembalikan tema-tema tentang Akhlaq, Suluk, atau Hal pada sumber Islam. Semuanya itu harus mempunyai landasan Al-Qur’an dan As-Sunnah.[17]
Satu hal mencolok yang dilakukan Al-Ghazali pada tasawuf adalah upayanya dalam mengalihkan tema-tema Dzauq (rasa), Tahliq (terbang), Syathahat, dan Tahwil
menjadi nilai-nilai yang peraktis. Ia mengobati hati dan bahaya jiwa,
lalu mensucikannya dengan akhlaq yang mulia. Upaya ini nampak jelas
terlihat dalam kitab Al-Ihya’-nya. Ia bebicara tentang akhlaq yang
mencelakakan(al-Muhlikat) dan akhlaq yang menyelamatkan (al-Munjiyat). “Al-Muhlikat adalah setiap akhlaq yang tercela (madzmum) yang dilarang al-Qur’an. Jiwa harus dibersihkan dari akhlaq yang tercela ini. Al-Munjiyat
adalah akhlaq yang terpuji (mahmud), sifat yang disukai dan sifatnya
orang-orang muqarrabin dan shiddiqin, dan menjadi alat bagi hamba untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam.[18]
Tema
ilmu sufi menurut Al-Ghazali adalah Dzat, sifat da perbuatan Alah SWT.
Adapun buah dari pengetahuan tentang Allah adalah timbulnya sikap
mencintai Allah, karena cinta tidak aka muncul tanpa “pengetahuan” dan perkenalan. Buah lain dari pengetahuan tentang Allah adalah “tenggelam dalam samudra Tauhid”,
karena seorang ‘arif tidak melihat apa-apa selain Allah, tidak kenal
selain Dia, di dalam wujud ini tiada lain kecuali Allah dan
perbuatan-Nya. Tidak ada perbuatan yang dapat dilihat manusia kecuali
itu adalah perbuatan Allah. Setiap alam adalah ciptaan-Nya. Barang siapa
melihat itu sebagai hasil perbuatan Allah, maka ia tidak meluhat
kecuali dalam Allah, ia tidak menjadi arif kecuali demi Allah, tidak
mencintai kecuali Allah SWT. Imam Al-Ghazali menambahkan, “Mereka
melatih hati, hingga Allah memperkenankan melihatNya. Sementara itu,
tasawuf dilakukan dengan memegang teguh dan mengamalkan Al-Qur’an dan
As-Sunnah.”[19]
Sehingga dalam perilaku dan ucapannya, Al-Ghazali teguh memegangi syari’at. Ia mengatakan, “seorang arif sejati mengatakan, “jika
kamu melihat seorang manusia mampu terbang di awang-awang dan mampu
berjalan di atas air, tetapi ia melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan syari’at, maka ketahuilah dia itu setan.”[20]
Bahkan
dengan terang-terangan dia menolak dan melawan mereka deangan berbagai
alasan dan dalil. Secara terus terang menyatakan seseorang yang telah
mendapatkan penyingkapan (kasyf) dan penyaksian (musyahadah) tidak layak
mengeluarkan suatu ucapan yang bertentangan dengan aqidah Islam, yakni
aqidah tauhid murni yang membedakan mana Tuhan dan mana hamba, serta
menegaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan hamba adalah hamba. Itulah
aqidah yang dipegang teguh Al-Ghazali.[21]Al-Ghazali
mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh kaum sufi itu
boleh jadi masuk ke dalam kategori imajinasi (tawahhun) karena mereka
kesulitan dengan kata-kata tentang kebersatuan yang telah mereka capai.
Atau, boleh jadi, penggunaan istilah-istilah itu masuk kerangka
pengembangan dan perluasan istilah yang sesuai dengan tradisi sufi dan
para penyair. Mereka biasanya meminjam istilah yang paling mudah
dipahami, seperti kata penyair berikut; “Aku adalah yang turun, dan yang turun adalah aku juga. Kami adalah ruh yang bersemayam dalam satu badan”.[22]
Lebih
jauh, Al-Ghazali mengambil kesimpulan secara umum denga memberikan
catatan penting yang menyatakan bahwa kebersatuan dengan Tuhan (ittihad)
secara rasional tidak mungkin terjadi. Dan Al-Ghazali tidak membahas
lebih lanjut ihwal makrifat intuitif (al-ma’rifah adz-dzawiqiyyah), yang merupakan konsep utama tasawufnya. Sebab, Al-Ghazali, sebagaimana di katakana oleh Ibnu Thufail,
telah terasah dengan berbagai ilmu dan terpoles dengan ma’rifat. Karena
itu, pembahasan Al-Ghazali tentang konsep ma’rifat senantiasa berada
dalam batas-batas agama. Ia tidak pernah membiarkan dirinya hanyut dalam
ucapan orang lain.[23]
Jadi,
dapat disimpulkan bahwa tasawuf menurut Al-Ghazali adalah mengosongkan
hati dari segala sesuatu selain Allah, menganggap rendah segala sesuatu
selain Allah, dan akibat dari sikap itu mempengaruhi pekerjaan hati dan
anggota badan.[24]
B. Al-Ghazali dan Syari’at
Sebagaimana
dipaparkan di atas tentang kehidupan Al-Ghazali bahwa, kehidupannya
diliputi gelombang pemikiran yang sangat dahsyat sehingga membuat
Al-Ghazali terombang-ambing dengan keyakinannya, maka dengangan demikian
terlontarlah kata-katanya yang bijak bahwa, “hingga akhirnya ia merasa
dirinya tidak lagi harus memilih, tetapi harus dipakasa untuk
meninggalkan Bagdad. Kini lidahnya menjadi berat dan dirinya merasa
bosan mengajar. Keadaan ini membuat hatinya sedih dan kondisi fisiknya
lemah, sampai-sampai dokter putus asa mengobatinya. Para dokter
mengatakan, “penyakitnya bersumber dari hati dan merembet ke tubuhnya.
Penyakitnya tidak bisa diobati kecuali mengistirahatkan pikiran dari
faktor-faktor yang membu atnya sakit”[25]
Mengenai
goncangan kepercayaan yang dipandang sesat dari ajaran Syi’ah
Bathiniyah atau yang beliau sebut golongan Ta’limiyah, yang mengharuskan
percaya kepada iman-iman yang dipandang ma’sum (terpelihara dari
kesalahan), Al-Ghazali menganjurkan agar masyarakat muslim lebih baik
beriman kepada Nabi Muhammad yang memang diwajibkan seluruh muslim
langsung beriman kepada Nabi, dan bukannya iman-iman kepada penyebar
bid’ah.[26]
Dari
susunan Ihya’ ‘Ulum al-Dien tergambar pokok pikiran Al-Ghazali
mengenai hubungan syariat dan hakekat atau tasawuf. Yakni sebelum
mempelajari dan mengamalkan tasawuf orang harus memperdalam ilmu tentang
syari’at dan aqidah telebih dahulu. Tidak hanya itu, dia harus
konsekuwen menjalankan syari’at dengan tekun dan sempurna. Karena dalam
hal syari’at seperti shalat, puasa dan lain-lain, di dalam ihya’
diterangkan tingkatan, cara menjalankan shalat, puasa, dan sebagainya.
Yakni sebagai umumnya para penganut tasawuf dalam ihya’ dibedakan
tingkatan orang shalat antara orang awam, orang khawas, dan yang lebih
khusus lagi. Demikian juga puasa, dan sebagainya. Sesudah menjalankan
syari’at dengan tertib dan penuh pengertian, baru pada jilid ketiga
dimulai mempelajari tarekat. Yaitu tentang mawas diri, pengendalian
nafsu-nafsu, dan kemudian lau wiridan dalam menjalankan dzikir, hingga
akhirnya berhasil mencapai ilmu kasyfi atau penghayatan ma’rifat.[27]
- C. Tasawuf dan Syari’at
Salah
satu tuduhan yang kerap dialamatkan kepada tasawuf adalah bahwa tasawuf
mengabaikan atau tidak mementingkan syari’at. Tuduhan ini berlaku hanya
bagi kasus-kasus tertntu yang biasanya terdapat dalam tasawuf tipe “Keadaan Mabuk”(sur, intoxication), yang dapat membedakan dari tasawuf tipe “keadaan-tidak-mabuk”(sahw, sobiety). “Keadaan Mabuk”
dikuasai oleh persaan kehadiran Tuhan: para sufi melihat Tuhan dalam
segala sesuatu dan kehilangan kemampuan untuk membedakan
makhluq-makhluq. Keadaan ini disertai oleh keintiman (uns), kedekatan
dengan Tuahn yang mencintai. “keadaan-tidak-mabuk” dipenuhi
oleh rasa takut dan hormat (haybah), rasa bahwa Tuhan betapa agung,
perkasa, penuh murkan dan jauh, derta tidak perduli pada
persoalan-persoalan kecil umat manusia.
Para sufi “yang mabuk” merasakan keintiman denga Tuhan dan sangat yaqin pada kasih sayangNya, sedangkan para sufi “yang-tidak-mabuk”
dikuasai rasa takut dan hormat kepada Tuhan dan tetap khawatir terhadap
kemurkaanNya. Yang pertama cenderung kurang mementingkan syari’at dan
menyaatkan terang-terangan persatuan denagan Tuhan, sedangkan yagn kedua
memelihara kesopanan (adab) terhadap Tuhan. Para sufi yang, dalam
ungkapan Ibn al-‘Arabi, “melkihat dengan kedua mata” selalu memelihara
akal dan kasyf (penyingkakpan intuitif) dalam keseimbangan yang sempurna
dengan tetap mengakui hak-hak “yang tidak-mabuk” dan “yang-mabuk.”
Tuduhan bahwa tasawuf mengabaikan syari’at tidak dapkat diterima apabila ditujukan kepada tasawuf tipe “keadaan-tidak-mabuk”.
Pasalnya, tasawuf tipe ini sangat menekankan pentingnya syari’at.
tasawuf tidak dapat dipisahkan karena bagi para penganutnya syri’at
adalah jalan awal yang harus ditempuh untuk menuju tasawuf.
Dalam
suatu bagian Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibn Al-‘Arabi menyatakan, “jika
engkau betanya apa itu tasawuf? Maka kami menjawab, tasawuf adalah
mengikatkan diri kepada kelakuan-kelakuan baik menurut syri’at secara
lahir dan batin dan itu adalah akhlaq mulia. Ungkapan-ungkapan kelakuan
baik menurut syari’at dalam perkataan Ibn al-‘Arabi ini menunjukkan
bahwa tasawuf harus berpedoman pada syari’at. Menurut sufi ini, syari’at
adalah timbangan dan pemimpin yang harus di ikuti dan disikuti oleh
siapa saja yang mengigninkan keberhasialan tasawuf. Sebagai mana Ibn
al’Arabi, Hussen Naser, seorang pemikir dari Iran yang membela tasawuf
tipe “keadaan-tidak-mabuk”berulangkali menekankan bahwa tidak ada
tasawwuf tanpa syari’at.
Iskam sebagai agama yang sngat menekankan
keseimbangan memanifestasikan dirinya dalam kesatuan syari’at (hukum
Tuahan) dan tharikat (jalan spiritual), yang sering disebut sufisme atau
tasawuf. Apabila syari’ata adalah dimensi eksoteris Islam, yang kebih
banyak berurusan aspek lahiriyah, maka tharikat adalah dimensi esoteric
Islam, yang lebih banyak berurusan dengan aspek bathiniyah. Pentingnya
menjaga keatuan syari’at dan tharikat dituntut oleh kenyataan bahwa
segala sesuatu dialam ini, termasuk manusia, mempunyai aspek lahitaiyah
dan bathiniyah.
Islam adalah suatu Agama yang mempunyai ajaran
yang amat luas. Ajaran-ajaran Islam itu dinamakan Syari’at Islam.
Syari’at Islam mencakup segenap peraturan-peraturan Allah SWT, yang
dibawa/disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, untuk seluruh manusia, dalam
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan menusia sesamanya dan
hubungannya dengan makhluk lain. Dan peraturan itu berfaedah untuk untuk
mensucikan jiwa manusia danmenghiasinya dengan sifat-sifat yang utama.
Inilah pengertian syari’at yang biasa dipakai oleh para Ulama’ Salaf.[28]
Tasawuf
adalah satu cabang dari Syari’at Islam, seperti halnya dengan
Tauhid(aqidah) dan fiqih yang merupakan cabang dari Syari’at Islam.
Seperti di dalam hadist yang diriwayatkan dari Umar ra, yang
mengisayaratkan tiga unsure dasar syari’at Islam tentang Islam, Iman dan
Ihsan. [29]
Ihsan
termasuk amal hati dalam hubungan dengan ma’bud(Tuhan). Soal ini tidak
dipelajari di dalam ilmu kalam dan fiqh, tetapi dibicarakan di dalam
Tasawuf. Adapun yang berkenaan dengan amal lahir seperti shalat, puasa,
zakat dan haji, itulah yang dipelajari dalam ilmu fiqh, yang menyangkut
soal aqidah dipelajari di dalam ilmu Kalam.[30]
Selain
dari Ihsan, tasawuf juga membahas tentang hubngan manusia dengan
sesamanya yang disebut akhlaq, seperti halnya dengan fiqh selain
membahas tentang rukun Islam ia juga membahas tentang muamalat maliah,
jinayat, munahkat dan qoda’, karena persoalan-persoalan ini erat
hubungannya dengan maslah pokok yang disebutkan Nabi diatas(Islam, Iman,
Ihsan). Sebagai contoh adalah tentang penyakit dengki(hasad). Dengki
menurut hadist Rasul dapat memakan amal seprti api memakan kayu bakar.
Dari hadist ini (tentang Islam, Iman, Ihsan)dapat dipahamkan bahwa
dengki yang merusak hubungan dengan sesame manusia juga dapat merusak
hubungan dengan Tuhan. Karena itu masalah akhlaq yang tercela dan akhlaq
yang terpuji yang bertumbuh di dalam hati dapat dipelajari dalam ilmu
Tasawuf. Dengan ini jelas, betapa kedudukan Tasawuf denga rangkaian
syari’at Islam.[31]
Tasawuf
Islam tidak akan ada kalau tidak ada Tauhid. Tegasnya tiada guna
pembersihan hati kalau tidak beriman. Tasawuf Islam sebenarnya adalah
hasil dari aqidah yang murni dan kuat yang seseuai dengan kehendak Allah
dan RasulNya.[32]
Sungguh
sudah banyak penganut Tasawuf yang tergelincir di bidang ini. Banyak
para Shufi yang telah mengaku dirinya Tuhan atau manifestasi Tuhan. Ada
pula yang mengaku bahwa para Nabi lebih rendah derajatnya dari para
wali. Ada yang mengi’tikadkan bahwa ibadat-ibadat yang kita kerjakan
tidak sampai kepada Tuhan kalau tidak dengan merabithahkan guru lebih
dahulu. Dan bayak macam-macam I’tiqad yang sesat yang bersumber dari
akal fikir manusia.[33]
Mereka
tidak melakukan segala I’tiqad-I’tiqad kafir dan musyrik ini kurang
mendalami jiwa Tauhid Islam yang murni/yang belum bercampur dengan
filsafat pemikiran manusia. Oleh sebab itu untuk mendalami tasawuf Islam
terlebih dahulu harus dimatagkan pengertian Tauhid Islam. Amal Tasawuf
akan rusak binasa kalau tidak didahului oleh pengertian tentang Tauhid.[34]
Demikianlah
hubungan antara ilmlu Tasawuf dengan ilmu Tauhid (syari’at). Tasawuf
tidak aka nada kalau tidak ada Tauhid dan Tauhid tidak akan tumbuh subur
dan berbuah lebat kalau tidak ada Tasawuf.[35]
- D. Kodifikasi TASAWUF dengan SYARI’AT dalam Kacamata AL-GHAZALI
Imam
Al-Ghazali (w, 111 M.) adalah ulama’ ahli syari’at penganut mazhab
syafi’I dalam hukum fiqh, dan seorang teolog pendukung Asy’ari yang
sangat kritis, namun sesudah lamjut usia ia mulai meragukan dalail akal
yang menjadi tiang tegaknya mazhab asy’ariah di samping dalil wahyu.
Sesudah mengalami keraguan terhadap kemampuan akal baik dalam filsafat
ataupun penggunaannya dalam ilmu kalam, akhirnya justru mendapat
kepuasan dalam penghayatan kejiwaan dalam sufisme, mempercayai
kemutlakan dalail kasyf. Hal ini merupakan keunikan atau keanaehan
al-Ghazali. Mungkin karena pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat
Persi masa itu yang merupakan lahan yang subur bagi perkembangan
pemikiran dan kehidupan sufisme. Agaknya beliau telah sejak kecil punya
penilaian positif terhadap ajaran sufisme. Karena memang beliau melihat
dan menghayati betapa institusi tasawuf dapat memperdalam keyakinan dan
perasaan agama yang mendalam, serta dapat membina akhlaq yang luhur. Dan
ternyata akhirnya Al-Ghazali jadi propagandis sufisme yang paling
bersemangat dan paling sukses. Misalnya, tetntang kehidupan para sufi
dan tasawuf yang digambarkannya:
“Sungguh aku
mengetahui secara yakin bahwa para sufi itulah orang-orang yang
benar-benar telah menempuh jalan Allah SWT, secara khusus. Dan bahwa
jalan mereka tempuh adalah jalan yang sebaik-baiknya, dan laku hidup
mereka adalah yang paling benar, dan akhlaq adalah yang paling suci.
Bahkan seandainya para ahli piker dan para filosof yang bijak, dan ilmu
para ulama yang berpegang pada rahasia syari’at berkumpul untuk
menciptkan jalan dan akhlaq yang lebih baik dari apa yang ada pada
mereka(para sufi) tidak mungkin bisa menemukannya. Lantaran gerak dan
diam para sufi, baik lahir ataupun bathin, dituntun oleh cahaya
kenabian. Dan tidak ada cahaya kenabian diatas dunia ini, cahaya lain
yang bisa meneranginya.”(mungqidz min al-Dlalal, hal, 31). [36]
Kutipan
di atas menunjukkan betapa tingginya nilai tasawuf di mata al-Ghazali.
Dan memang hingga masa itu tasawuf masih dikelola oleh golongan elit
(khawas), belum merakyat. Jadi kualitasnya masih bias terkendali. Hanya
timbulnya kecenserungan kea rah phanteis atau union-mistik dan
penyimpangan terhadap syari’at yang meulai memperihatinkan dan
menimbulkan ketegangan. Hal ini tercermin dalam judul risalah
otobiografi al-Ghazali al-Munqidz min ad-Dlalal, yang bias di
terjemahkan pembebas dari kesesatan. Dari segi sufuisme buku tersebut
mengkritik kesesatan peafsiran para penganut paham hulul, ittihad, dan
wushul, dengan pernyataannya:
“ringkasnya,
penghayatn makrifat itu memuncak sampai yang demikian dekatnya pada
Allah sehingga ada segolongan mengatakan hulul, segolongan lagi
mengatakan ittihad, dan ada pula yang mengatakan wushul, kesemua ini
salah. Dan telah kujelaskan segi kesalahan mereka dalam maqshudu
al-Aqsha(Tujuan yang Tinggi).Al-Munqidz min al-Dlala, hal. 32”[37]
Mengenai
goncangan kepercayaan yang dipandang sesat dari ajaran Syi’ah
Bathiniyah atau yang beliau sebut golongan Ta’limiyah, yang mengharuskan
percaya kepada imam-imam yang dipandang ma’sum (terpelihara dari
kesalahan), Al-Ghazali menganjurkan agar masyarakat muslim lebih baik
beriman kepada Nabi Muhammad yang memang diwajibkan seluruh muslim
langsung beriman kepada Nabi, dan bukannya iman-iman kepada penyebar
bid’ah. .[38]
Sedang
mengenai masalah ajaran-ajaran dalam sufisme, dalam munqidz telah
ditunjikkan paham-paham yang sesat. Agar masyarakat tidak tersesat
kepaham neka-neka al-Ghazali mencoba membatasi penghayatan makrifat
dalam sufisme agar dimoderasi hanhya sampai ke penghayatan yang amat
dekat dengan Tuhan, tidak terjerumus ke paham hulul, ittihad, dan
whusul. Dengan demikian berarti al-Ghazali menolak penghayatan makrifat
kea rah puncak, yaitu menolak fana’ al-fana’. Jadi dalam mengamalkan
tasawuf dibatasi dan dimoderasi hanya kepada penghayatan fana’ (ecstasy)
yang tengah-tengah, yang masih menyadari adanya perbedaan yang
fundamental antara manusia dan Tuhan yang transenden, mengatasi alam
semesta. Yaitu hanya samkpai penghayatan yang dekat (qurb) dengan Tuhan,
sehingga kesadaran diri sebagai yang sedang makrifat tetap berbeda
dengan Tuhan yang dimakrifatinya.[39]
Kemudian
soal pendalaman perasaan agama dan pemantapan iman, Al-Ghazali melihat
bahwa tasawuf adalah sarana yang hebat untuk untuk mendukung bagi
pendalaman rasa agama (spiritualitas Islam) dan untuk memantapkan dan
menghidupkan iman. Dengan ilmu kalam orang baru bisa mengerti tentang
pokok-pokok keimanan, namun tidak bisa menanamkan keyakinan yang mantap
dan menghidupkan pengalaman agama. Oleh karena itulah tasawuflah sarana
yang paling hebat untuk mengobati penyakit formalism dan kekeringan rasa
keagamaan ini menurut Al-Ghazali.[40]
Yang menjadi masalah kemudian, bagaimana cara mengawinkan dan
mengkompromikan tasawuf dengan syari’at itu? Atau dengan kata lain
bagaimana mengkompromikan syari’at dan hakikat sehingga keduanya tidak
saling menggusur, akan tetapi justru saling mendukung.?
Kebutuhan
ini wajar, karena para sufi sendiri mengembangkan ajaran mereka adalah
untuk menyemarakkan kehidupan agama, dan bukan untuk merusaknya. Namun
bagaimana caranya, itu yang belum bisa di kemukakan oleh para ulama’
sufi. Imam al-Qusyairi (w, 1074M.) dalam risalahnya baru bisa merumuskan
harapan sebagai berikut:
“Syari’at itu
perintah untuk melaksanakan ibadah, sedang hakikat menghayati kebesaran
Tuhan (dalam ibadah). Maka setiap syari’at yang tidak diperkuat dengan
hakikat tidak diterima; dan setiap hakikat yang tidak terkait dengan
syari’at, pasti tak menghasilkan apa-apa. Syari’at dating dengan
kewajiban pada hamba, dan hakikat memberikan ketentuan Tuhan. Syari’at
memerintahkan mengibadahi pada Dia. Syari’at melakuakan yang
diperintahkan Dia, hakikat menyaksikan ketentuanNya, kadarNya, baik yang
tersembunyi ataupun yang tampak diluar. (Risalah Qusyairiyah, hal. 46)”[41]
Walaupun
cita untuik menjalin keselarasan pengamalan taswuf dengan syari’at
telah di cetuskan dan menjadi keprihatinan ulama’-ulama’ sufi
sebelumnya, namun baru al-Ghazali yang secara konkrit berhasil
merumuskan bangunan ajarannya. Konsep al-Ghazali yang mengkompromikan
dan menjalin secara ketat antara pengalaman sufisme denga syari’at
disusun dalam karyanya yang paling monumental Ihya’ Ulumu ad-Din.[42]
Dari
susunan Ihya’ ‘Ulum al-Dien tergambar pokok pikiran Al-Ghazali
mengenai hubungan syariat dan hakekat atau tasawuf. Yakni sebelum
mempelajari dan mengamalkan tasawuf orang harus memperdalam ilmu tentang
syari’at dan aqidah telebih dahulu. Tidak hanya itu, dia harus
konsekuwen menjalankan syari’at dengan tekun dan sempurna. Karena dalam
hal syari’at seperti shalat, puasa dan lain-lain, di dalam ihya’
diterangkan tingkatan, cara menjalankan shalat, puasa, dan sebagainya.
Yakni sebagai umumnya p[ara penganut tasawuf dalam ihya’ dibedakan
tingkatan orang shalat antara orang awam, orang khawas, dan yang lebih
khusus lagi. Demikian juga puasa, dan sebagainya. Sesudah menjalankan
syari’at dengan tertib dan penuh pengertian, baru pada jilid ketiga
dimulai mempelajari tarekat. Yaitu tentang mawas diri, pengendalian
nafsu-nafsu, dan kemudian lau wiridan dalam menjalankan dzikir, hingga
akhirnya berhasil mencapai ilmu kasyfi atau penghayatan ma’rifat.[43]
Tema
ilmu sufi menurut Al-Ghazali adalah Dzat, sifat da perbuatan Alah SWT.
Adapun buah dari pengetahuan tentang Allah adalah timbulnya sikap
mencintai Allah, karena cinta tidak aka muncul tanpa “pengetahuan” dan
perkenalan. Buah lain dari pengetahuan tentang Allah adalah “tenggelam
dalam samudra Tauhid”, karena seorang ‘arif tidak melihat apa-apa
selain Allah, tidak kenal selain Dia, di dalam wujud ini tiada lain
kecuali Allah dan perbuatan-Nya. Tidak ada perbuatan yang dapat dilihat
manusia kecuali itu adalah perbuatan Allah. Setiap alam adalah
ciptaan-Nya. Barang siapa melihat itu sebagai hasil perbuatan Allah,
maka ia tidak meluhat kecuali dalam Allah, ia tidak menjadi arif kecuali
demi Allah, tidak mencintai kecuali Allah SWT. Imam Al-Ghazali
menambahkan, “mereka melatih hati, hingga Allah memperkenankan
melihatNya. Sementara itu, tasawuf dilakukan dengan memegang teguh dan
mengamalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.[44]
Sehingga
dalam perilaku dan ucapannya, Al-Ghazali teguh memegangi syari’at. Ia
mengatakan, “seorang arif sejati mengatakan, “jika kamu melihat seorang
manusia mampu terbang di awang-awang dan mampu berjalan di atas air,
tetapi ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari’at, maka
ketahuilah dia itu setan.”[45]
Referensi:
ü Tasawuf dan Perkembangannya Dalam Islam. Dr. Simuh. Jakarta. Rajawali Pers. Cet. II. Hal. Th. 2002.
ü Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Dr. Abdul Fattah Sayyid Ahmad. Khalifah Jakarta. Cet I. Th. 2000 M.
ü Tasawuf antara Agama dan Filsafat. Dr. Ibrahim Hilal. Pustaka Hidayah Bandung. Cet. I. Th. 2002.
ü Pengantar Ilmu Tasawuf. Drs. Yunasril Ali. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. Cet. I. Th 1987 M.
[1]. Tasawuf dan Perkembangannya Dalam Islam. Dr. Simuh. Jakarta. Rajawali Pers. Cet. II. Hal. 151. Th. 2002.
[2]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Dr. Abdul Fattah Sayyid Ahmad. Khalifah Jakarta. Cet I. hal. 69. Th. 2000 M.
[3]. Ibid
[4]. Simuh. Hal. 152
[5]. Simuh. Hal. 153
[6]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hal 95
[7]. Ibid 96
[8]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hal. 96
[9]. Ibid 97
[10]. Ibid
[11]. Ibid
[12]. Simuh. Hal 154
[13]. Simuh. Hal 155
[14]. Ibid. hal 158
[15]. Ibid
[16]. Simuh. Hal 159
[17]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hal 234
[18]. Ibid. hal, 236
[19]. Ibid.
[20]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hal 234
[21]. Tasawuf antara Agama dan Filsafat. Dr. Ibrahim Hilal. Pustaka Hidayah Bandung. Cet. I. hal. 89. Th. 2002.
[22]. Ibid. hal. 90
[23]. Ibid. hal 92.lihat juga ihya’ ‘ulumuddin, hal. 5, 25.
[24]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hal. 104
[25]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hal 98
[26]. Simuh. Hal 157
[27]. Ibid. 160.
[28] Pengantar Ilmu Tasawuf. Drs. Yunasril Ali. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. Cet. I. hal. 29. Th 1987 M.
[29] Ibid. hal. 30.
[30] Ibid. hal. 33.
[31]Drs. Yunasril Ali. Hal. 34
[32]Hal. 54
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid. hal. 36.
[36]. Simuh. Hal 155
[37] Simuh. Hal. 156
[38]. Simuh. Hal 157
[39] Simuh. Hal. 158
[40]. Ibid. hal 158
[41] SIMUH. Hal. 159
[42] Ibid
[43]. Ibid. 160.
[44]. Ibid.
[45]. Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Hal 234

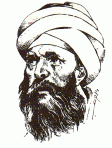 “Ketika
masih muda, aku menyelami samudera yang dalam ini. Aku menyelaminya
sebagai penyelam handal dan pemberani, buka sebagai penyelam penakut dan
pengecut. Aku menyerang setiap kegelapan dan mengatasi semua maslah,
menyelami kegoncangan.
“Ketika
masih muda, aku menyelami samudera yang dalam ini. Aku menyelaminya
sebagai penyelam handal dan pemberani, buka sebagai penyelam penakut dan
pengecut. Aku menyerang setiap kegelapan dan mengatasi semua maslah,
menyelami kegoncangan.
0 comments:
Post a Comment
Silahkan Tinggalkan komentar kamu